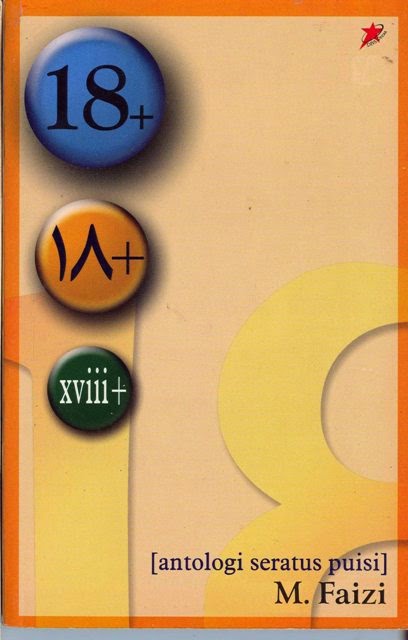GUS, BICARALAH!
- ambis
bicaralah, gus
siapa lagi di negeri ini
yang kata-katanya meneduhkan hati
maknanya menyejukkan kalbu
selain dirimu?
koran dan majalah mati
kecuali yang pinter memelintir nurani
membangun dunia hanya dengan satu mata
bersama radio yang sekarat di gendang telinga
televisi beternak bencong
pamer aib bersama politisi songong
cendekiawan ngomong sesuai pesanan
agamawan kawe disulap jadi perlente
nabi palsu bersurban kekuasaan
ditahbiskan oleh malaikat gadungan
lantas, jingkrak-jingkrak bersama para iklan
menyanyikan jingle kemewahan
usai ceramah dangkal di alam maya
tentang surga yang selalu memabukkan
atau neraka yang senantiasa mengerikan.
sambil merangket tuhan
mereka berebut ayat-ayat keutamaan
atas nama pribadi dan kaum segolongan
bicaralah, gus
siapa lagi di jaman sekarang
yang ucapannya menjernihkan pikiran
relung renungnya menebar pencerahan
selain sampeyan?
orang-orang sakau agama, mabuk keyakinan
tak mau menunduk, menoleh, melihat ke belakang
cuma menatap cakrawala, memandang bintang-bintang
sembarangan menumpah ibadah dan doa di jalanan
merakit ancaman, meledakkan teror kekerasan
berjubah kesalehan
orang-orang lupa jati diri
alergi imunisasi dini budi pekerti
memuja kebrutalan dan kedigdayaan massa
sambil tuna sejarah dan buta budaya!
orang-orang keranjingan fitnah
menumpuk kebenaran sampah
memulungnya dari jargon demokrasi kuda
menenggaknya bersama adonan kencing onta
bicaralah, gus
jangan cuma di leteh mengaji
menjamu tamu tiada henti
manggung dengan seniman gila dan selebriti wangi
bicaralah, gus
bicara
seperti dulu berseberangan dengan ayahmu demi patuh kepada
ibu
kautinggalkan kelas menghindari guru keras
kautolak parlemen yang menawarkan jabatan cemen
berbeda dari para kiai demi merangkul umat yang hakiki
bicaralah, gus
bicara
ibu bumi sendu sendiri
ditinggal putra-putri sejati
sebagian menghadap gusti
sebagian mati suri
yang lainnya malih rupa sengkuni
atau menjelma betara kala
demi mengisap madu dunia
bicaralah, gus
bicara...
solo, 7 agustus 2018
 |
| sumber: https://goo.gl/n7b9GK |
* * *
Ini adalah tafsir puisi saya untuk puisi Sosiawan Leak yang saya temukan di akun
Facebooknya tempo hari. Saya tidak tahu, puisi ini ditulis spontan atau bagaimana, atau dalam rangka apa. Datum penciptaannya masih baru, yakni 7 Agustus 2018.
#tafsirpuisimanasuka
"Gus, Bicaralah!"
- ambis
bicaralah, gus (maksudnya, berikan tausiah atau petuah atau
arahan, tentang keteladanan tentunya, atau fatwa apa pun yang menenteramkan di
saat sekarang situasinya serba memantik perseteruan)
siapa lagi di negeri ini
yang kata-katanya meneduhkan hati
maknanya menyejukkan kalbu
selain dirimu? (penyair Sosiawan Leak menganggap “Gus” ini sebagai
satu-satunya orang yang layak dimintai nasehat. Siapakah “Gus” ini? Kita belum
tahu, kita ikut saja. Entah. Tapi, pada dasarnya, gaya seperti ini hanya bentuk
penyangatan saja, hiperbola. Barangkali, yang dimaksudkannya adalah bahwa sudah
sangat jarang orang yang seperti dia, sangat jarang, sehingga dia mengambil
kesimpulan statemen pendek saja: satu-satunya)
koran dan majalah mati (tidak laku, omset dan oplah menurun,
dan mungkin mati beneran, tidak terbit lagi)
kecuali yang pinter memelintir nurani (yang berpihak kepada
pemodal dan/atau penguasa, meskipun bertentangan dengan suara hati nurani
dirinya, apalagi nurani bangsa. Media yang demikian itu akan)
membangun dunia hanya dengan satu mata (sehingga kebenaran
tampak tunggal dan tidak dapat ditafsirkan)
bersama radio yang sekarat di gendang telinga (jarang
didengarkan atau nasibnya mengenaskan. Heren, mengapa penyair menggunakan radio
sementara saat ini jarang sekali orang menggunakan ikon tersebut sebagai bagian
dari sumber berita)
Nyatanya, bukan hanya nasib kedua media [cetak] tersebut
yang kacau. Media lainnya pun bernasib sama, termasuk media elektronik, seperti
radio. Sementara media elektronik yang menguasai pangsa pasar arus utama media saat
ini, di Indonesia, tetaplah televisi. Dan ironisnya, sajian dan tayangnnya
ampang, tidak mendidik, penuh hura-hura, yaitu ),
televisi beternak bencong (kurang paham, penyairlah yang
tahu ke referensi apa/mana ini maksud kalimat ini diarahkan. Mungkin si penyair
sangat emosional saat menulis bagian ini)
pamer aib bersama politisi songong (konon, banyak contohnya
yang begini dan selalu tayang di televisi [Maaf, saya tidak pernah menontonnya
karena memang tidak punya tivi])
cendekiawan ngomong sesuai pesanan (padahal cendekiawan itu mestinya
menjunjung tinggi etika kesarjanaan dan intelektualitasnya, tapi mungkin
terjadi di lapangan adalah mereka yang ngomong sesuai selera ‘pemesan’-nya)
agamawan kawe disulap jadi perlente (orang yang tidak
betul-betul paham agama tetapi industri yang mengarahkannya dan menuntutnya
demikian karena—misalnya—unsur selebritasnya yang moncer duluan)
nabi palsu bersurban kekuasaan (“nabi palsu” bisa dipahami
literal, yaitu orang yang memang mengaku mendapatkan wahyu dan menjadi nabi di
era milineal; juga mungkin tokoh panutan yang sebetulnya memiliki banyak rekam
jejak gelap tetapi disembunyikan kepada publik demi publisitas dan, lagi-lagi,
industri hiburan dan rating)
ditahbiskan oleh malaikat gadungan (karena palsu, maka
sumber ‘wahyu’-nya pasti juga palsu. Apa benar begitu? Kita tidak tahu. Akan tetapi,
ada indikator yang menunjukkan. Salah satunya adalah hilangnya muruah, di
antaranya)
lantas, jingkrak-jingkrak bersama para iklan
menyanyikan jingle kemewahan (iklan dan jingle kemewahan adalah
pendamping kepalsuan mereka semua, ini adalah penyangatan yang dilakukan
penyair agar kepalsuannya semakin jelas)
usai ceramah dangkal di alam maya (yang dimaksud “dangkal” adalah
persoalan yang terlalu sepele untuk dibahas oleh seorang tokoh agama atau
persoalan yang sangat prinsip tetapi dipahami dengan apa adanya. Yang pertama
menurunkan derajat kewibawaan pengetahuan keilmuan. Yang kedua malah bahaya
karena bisa menyesatkan. Kasus yang kerap terjadi adalah slogan kembali ke
Alquran dan Hadis. Apa ini salah? Sangat benar, tetapi tentu saja harus memiliki
kapasitas keilmuan yang memadai. Mengapa kita hanya ikut ulama? Karena kita
meyakini kemampuan mereka dalam memahami agama dan/atau mereka merujuk kepada
referensi utama dari ulama yang mumpuni dan tidak diragukan lagi dalam cara
beristinbat dari kedua rujukan utama umat Islam tersebut, beda dengan kita-kita
dan seleb-seleb kita yang modalnya terkadang hanya terjemahan).
tentang surga yang selalu memabukkan
atau neraka yang senantiasa mengerikan (dua hal ini memang
sepasang tema yang selalu dibicarakan bersama-sama: surga dengan segala
kenikmatannya dan neraka dengan segala kesengsaraannya. Kedua tema demikian
masyhur dalam redaksi ayat, sabda nabi, maupun kaul para ulama).
sambil merangket tuhan
mereka berebut ayat-ayat keutamaan
atas nama pribadi dan kaum segolongan (oleh karena telah menjadi
bagian dari industri dan tontonan, dikungkung oleh banyaknya kepentingan
politik dan kekuasaan, maka tidak heran apabila fatwa yang disampaikan,
meskipun menggunakan ayat-ayat suci dan hadis nabi, bisa saja diplintir dan
dicarikan ‘hailah’-nya demi kepentingan sesaat, kepentingan kelompok dan
golongan dan pemesannya. Kira-kira demikian maksud penyair pada bagian ini)
bicaralah, gus
siapa lagi di jaman sekarang
yang ucapannya menjernihkan pikiran
relung renungnya menebar pencerahan
selain sampeyan? (bait ini jelas, tidak perlu ditafsirkan.
Tapi, perlu diwaspadai pula, bahwa frase “selain sampeyan” di sini artinya
“bahwa meskipun bukan satu-satunya, tidak banyak lagi orang yang seperti Anda”.
Bagian ini perlu dijelaskan untuk mengantisipasi adanya pamahaman literal atau pandangan
polos dari pembaca yang menganggap ungkapan ini sebagai ungkapan biasa, bukan
ungkapan puitis. Kita harus mengacu kepada gaya bahasa sinekdoke, menyebut sebagian
tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan atau seluruhnya dengan maksud sebagian)
orang-orang sakau agama, mabuk keyakinan (sakau adalah
kondisi orang yang sedang ketagihan narkoba; terkadang dianggap sebagai akronim
daripada “sakit karena putau”. Ketika sakau disandingkan dengan kata agama,
sepintas ia berkaitan dengan ucapan Karl Marx, “agama adalah candu bagi masyarakat”,
tapi jelaslah ini bukan demikian maksudnya. Ini tentang orang yang suka
memelintir kepentingan sebagaimana dijelaskan pada bait-bait sebelumnya. Lagi
pula, ungkapan Marx itu ternyata juga korban pelintiran, sama dengan ungkapan “mens
sana in corpore sano” yang juga plitiran, diambil sepenggal sehingga yang
semula berorientasi religius [karena lengkapnya berbunyi: “orandum es ut it,
mens sana in corpore sano” yang artinya “berdoalah agar kamu punya akal sehat
di tubuh yang sehat”] berubah mendadak jadi materialistik. Begitu pula dengan
statemen Marx: “Die Religion ist... das Opium des Volks”, padahal yang lengkap
adalah “Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer
herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium
des Volks” yang artinya kurang lebih: Agama adalah desah napas keluhan yang
muncul dari makhluk yang tertekan, hati daripada dunia yang tak punya hati, dan
ia adalah jiwa bagi kondisi-tak-berjiwa. Ia adalah opium bagi masyarakat."
Karena Marx menggunakan opium dan opium adalah jenis
narkotika yang berarti negatif, maka statemen ini menjadi peyor, mengandung
kesan miring. Namun, kalau opium yang dimaksud Marx di sini adalah efek kerja
opium yang dapat melepaskan katup katarsis orang yang sedang tertekan oleh
kehidupan profan yang wadag dan kejam, maka muluslah anggapannya. Dalam konteks
ini, Sosiawan Leak menganggap ustad yang menurutnya sudah sakau dan mabuk ini
tidak dapat membedakan lagi kebenaran pokok dan kebenaran cabang. Mana yang
ushul, mana yang furu’, yang penting dia yang harus benar, karena orang seperti
itu adalah orang yang tidak “tahu diri”, dengan ciri-ciri)
tak mau menunduk (tawaduk), menoleh (tidak melihat muqtadal
hal, situasi dan konteks), melihat ke belakang (tidak merenungkan masa
silam)
cuma menatap cakrawala, memandang bintang-bintang (hanya
berandai dan melihat hal-hal yang terlalu tinggi)
sembarangan menumpah ibadah dan doa di jalanan
merakit ancaman, meledakkan teror kekerasan
berjubah kesalehan
(ketiga baris ini adalah metafora bagi keadaan di mana
orang-orang lebih gemar melihat yang tampak daripada mahia, daripada inti
permasalahan. Dan kondisi seperti ini masih diteruskan oleh si penyair pada
bait berikutnya)
orang-orang lupa jati diri (lupa siapa dirinya, sebagai
bangsa dan sebagai warga negara)
alergi imunisasi dini budi pekerti (tidak mau menjaga budi
pekerti, sehingga tidak kebal terhadap serangan penyakit hasud dan iri dengki. Karena
sudah demikian keadaannya, maka mereka)
memuja kebrutalan dan kedigdayaan massa (mereka berani bertindak
ngawur karena mempunyai kekuatan massa, tapi si penyair menyayangkan mereka
bergerak namun)
sambil tuna sejarah dan buta budaya! (yang artinya, tidak
tahu benar bagaimana sejarah negara-bangsa Indonesia ini dibangun oleh para
pendiri, para leluhur)
orang-orang keranjingan fitnah (bagian ini masih lanjutan
dari yang dikeluhkan, seperti pada bait sebelumnya, yaitu mereka yang)
menumpuk kebenaran sampah (seolah benar, padahal palsu; hoax)
memulungnya dari jargon demokrasi kuda
menenggaknya bersama adonan kencing onta
(kiranya, frase “demokrasi kuda” dan “kencing onta” mengacu
pada referensi tertentu, bukan referensi yang umum diketahui orang. Maka dari
itu, saya tidak menafsir lebih jauh karena bagian ini bersifat “tertutup”,
hanya si penyair yang seperti tahu benar-benar dari yang dikehendaki daripada
frase ini)
bicaralah, gus
jangan cuma di leteh mengaji (Oh, Gus di sini Gus Mus, tho?
Ya, baru sampai di sinilah ketahuan, bahwa yang dimaksud “Gus” dalam puisi ini
adalah Gus Mus karena beliau tinggal di Leteh, Rembang, tentu dengan tanpa
menafikan kiai lain yang tinggal di sana)
menjamu tamu tiada henti
manggung dengan seniman gila (maksudnya seperti Sosiawan
Leak, he, he, sepurane, Mas) dan selebriti wangi (dan artis yang sering tampil
di televisi, artis ibukota]
bicaralah, gus
bicara (diulang lagi, repetisi)
seperti dulu berseberangan dengan ayahmu demi patuh kepada
ibu (ini tentu berkaitan khusus dengan cerita Gus tentang beda pendapat
terhadap orangtuanya, mungkin beda pendapat soal remeh-temeh atau apa pun,
tidak jelas, harus merujuk pada cerita langsung dari sumber rujukan)
kautinggalkan kelas menghindari guru keras (dan ini adalah
satu dari bagian cerita itu, sebagaimana juga ditunjukkan dalam wujud sikap konsisten
untuk tidak ikut-ikutan arus jika hal itu dianggap tidak tepat, apalagi sesat,
seperti)
kautolak parlemen yang menawarkan jabatan cemen (padahal, kebanyakan
orang menganggap bahwa menjadi anggota parlemen adalah jabatan yang tidak cemen;
ini gaya ironi)
berbeda dari para kiai (yang berbeda pendapat dengan beliau,
para kiai yang mungkin mau diajak kompromi dengan kekuasaan dengan iming-iming harta
dan jabatan. Semua itu dilakukan si Gus ini) demi merangkul umat yang hakiki
(umat yang memang butuh bimbingannya, bukan umat yang butuh bimbingan kalau
sama kepentingan tetapi menolak kalau beda tujuan, apalagi tidak menguntungkan)
bicaralah, gus
bicara (diulang lagi, repetisi, sama seperti yang
sudah-sudah)
ibu bumi sendu sendiri (maksudnya Ibu Pertiwi, Indonesia, yang
kini dalam keadaan sedih)
ditinggal putra-putri sejati (bagian ini mengacu kepada lagu
“Kartini”, pahlawan asal Rembang, bahwa banyak tokoh bangsa yang telah mangkat,
dan)
sebagian menghadap gusti (alias wafat)
sebagian mati suri (yakni tidak berdaya, baik secara jasmani
maupun secara politis)
yang lainnya malih rupa sengkuni (dan sebagian lagi malah
berkhianat, seperti dalam wujud yang lain, yakni tokoh antagonis yang lain)
atau menjelma betara kala
demi mengisap madu dunia
bicaralah, gus
bicara...
(diulang lagi, sepertinya ini menunjukkan itikad si penyair
untuk ‘memaksa’ Gus agar bersuara lebih lantang lagi, atau sekadar bentuk harapan
yang sangat besar kepadanya. Wallahu a’lam)
solo, 7 agustus 2018